Tulisan
ini tak akan hadir tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul kala
berkendara motor di area Purwokerto dan Banyumas. Kadang, menjadi
manusia berusia 22 tahun yang sedang berjuang dengan tugas akhirnya
merasa sudah menjadi bijak dan dewasa. Padahal, makhluk kecil seperti
saya belum ada apa-apanya dengan para orangtua yang berjuang dan
berpikir keras untuk masa depan anak kesayangan di tengah himpitan kemiskinan. Belum ada apa-apanya dengan CEO-CEO startup muda dengan tekanan
politik bisnis, atau bahkan rekan seperjuangan skripsi yang was-was
menunggu ruang tunggu dosen dengan kertas penuh corat-coret di
tangannya.
Semenjak
memasuki semester tujuh, tiada hari tanpa terbangun tanpa memikirkan
tugas akhir dan segala kemungkinan pasca wisuda nanti. Di tengah
atmosfir yang warna-warni ini, menjadi pribadi yang belajar bijak adalah
satu-satunya pilihan. Harus pandai memilah kata terutama kepada teman
seperjuangan, harus bisa membuktikan kalimat motivasi dan niatan yang
keluar dari mulut sendiri, dan menjadi pribadi yang penuh tanggungjawab
akan tubuh dan pikirannya sendiri.
Ah,
masalah hidup mahasiswa semester akhir mah gitu-gitu aja. Nanti juga
terlewatkan, masih banyak rintangan lebih berat di depan.
Benar.
Kalimat tersebut juga sempat saya amini dengan kemudian mengabaikan
banyak teman yang mendahului seminar. Tentu saja hal tersebut adalah
salah jika hanya meluruskan perspektif diri sendiri. Kita, atau berawal
dari pengalaman saya sendiri misalnya bukan hanya perlu menengok
sebentar siapa saja orang-orang yang mengharapkan lekas wisuda, namun
juga duduk sejenak sembari berkontemplasi agar ketika kaki mulai
melangkah lagi tak akan berpindah haluan fokus.
Mari
kembali ke perenungan-perenungan. Tiba-tiba terbesit dalam kepala saya
betapa manusia hidup adalah tentang pencarian makna. Pencarian tanpa
ujung yang membuatnya (atau kadang memaksa) untuk terus berjalan. Toh,
memang sepertinya pada akhirnya akan menemui titik yang serupa. Dalam
lingkaran saya yang masih kecil ini, saya memahami betapa masing-masing
individu manusia memiliki indikatornya masing-masing. Sekalipun bagi
yang tak memegang prinsip mengikuti standar sosial.
Indikator-indikator
tersebut adalah bentuk ukuran kebahagiaan dan ketidakbahagiaan.
Masing-masing memiliki definisi akan sebanyak apa ukuran tersebut.
Misalnya seseorang akan merasa kurang puas ketika seharian hanya bermain
dengan gadgetnya yang sebenarnya sangat nikmat
untuk dilakukan. Kemudian memaksa dirinya untuk banyak melakukan banyak
aktivitas dan menurutnya hal tersebut lebih bermakna dan bernilai. Namun
ada juga yang memilih untuk menyendiri di ruang kecilnya untuk menulis
karya-karya kemudian memajangnya di media sosial dengan harapan dapat
memengaruhi pemikiran orang lain. Hal tersebut, sekali lagi menjadi
bermakna dan bernilai bagi masing-masing individu memang berbeda
ukurannya.
Buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, Catatan Seorang Demonstran, podcast Menjadi Manusia yang berjudul Menjadi Manusia Lamban dan Sabtu Pagi menjadi
beberapa teman saya dalam mengolah pikiran. Untuk sekian jeda saya
setuju dengan beberapa pendapat dan sisanya saya mengambil jeda lagi.
Nampaknya, Tuhan sengaja menciptakan jeda untuk berkontemplasi lebih
banyak agar lebih bijak lagi mengolah pikiran. Lantas timbul lagi
pertanyaan seperti “apakah Tuhan sengaja menciptakan
kemiskinan? Apakah untuk membentuk gerakan yang masif hanya melalui
politik sebagai satu-satunya jalan”. Sambil ditemani lagu “Someday”nya Steve Earle yang sudah saya dengarkan sejak mengenal film Bridge to Terabithia saya berujar “hidup ternyata lumayan sekompleks itu ya”. Dari situ kemudian saya bukan lagi paham mengenai frasa memanusiakan manusia namun rindu menjadi manusia.
Mungkin, selalu ada yang harus kita bayar untuk memaknai menjadi manusia. Selalu ada, seminimalis apapun itu.
Untuk tetap bisa berjumpa misalnya, individu harus lebih lama tinggal
dan menunggu. Untuk mendapat pengakuan misalnya, individu banyak
melakukan banyak hal meskipun putus asa — orang tak akan menganggapnya
putus asa karena dia tak diam. Untuk menikmati kebahagiaan barang
sedikit saja misalnya, individu harus membangun dan memiliki tameng yang
begitu kokoh untuk memersiapkan perpisahan atau kemungkinan-kemungkinan
terburuk. Menjadi bagian, menjadi pilihan. Karena demi apapun,
orang-orang mungkin tak sepenuhnya peduli pada apa yang kita lakukan
sekalipun hal tersebut bermakna dan bernilai bagi kita. Mereka juga
mempunyai perkara proses masing-masing. Lantas, apa yang terus membuat
kita tetap melakukan hal-hal tersebut? Sebuah alasan untuk tetap hidup
dan maju? Menjalani peran atau lakon? Menjaga kewarasan? Perlu dan
menciptakan hati yang diciptakan untuk besar dan ikhlas dalam menyikapi
bahwa kita sedang bersama-sama berproses dalam romantisme perjuangan
masing-masing.
‘Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan’ — Sutan Sjahrir
***
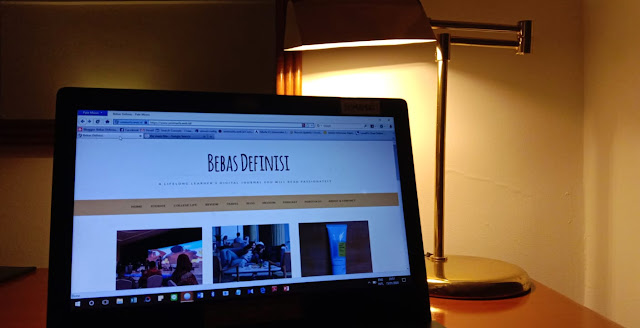


Write a comment
Posting Komentar
Halo, terima kasih sudah berkunjung!^^ Mohon klik 'Notify Me/Beri Tahu Saya' utk mengetahui balasan komentar via email.